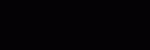Pada 2003, wayang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan—sebuah seni yang memadukan keindahan rupa, gamelan, dan filosofi hidup. Bagi orang Jawa, wayang adalah wewayanganing urip—bayangan kehidupan, kisah yang menuntun sekaligus menghibur.
Di antara berbagai bentuknya, Wayang Gedhog menonjol dengan kisah Panji, pangeran legendaris dari Jawa Timur. Pernah gemilang di lingkungan istana, kini ia menjadi jejak berharga dari budaya yang terus bertransformasi seiring waktu.






Disadur dari buku Seri Pustaka Wayang Nusantara I, “Pakem Pakeliran Wayang Gedhog Gaya Yogyakarta”, Rudy Wiratama.
Sebagai warisan dunia, wayang mencerminkan bayangan kehidupan. Di antara bentuknya, Wayang Gedhog dari kisah Panji menyingkap keindahan dan perubahan budaya Jawa dari masa ke masa.
Pengakuan dunia lewat UNESCO ini bukan hanya karena keindahan seni rupa boneka kulitnya yang rumit dan iringan gamelan yang megah, tetapi juga karena kedalaman cerita, nilai, dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Bagi orang Jawa, wayang adalah wewayanganing urip—bayangan kehidupan—sebuah tontonan yang sekaligus tuntunan, yang mampu menghibur sekaligus membersihkan jiwa, serupa dengan fungsi drama klasik di Yunani.
Di antara berbagai cabang dunia pewayangan, ada satu bentuk yang unik tetapi kini jarang dikenal: Wayang Gedhog, sebuah pertunjukan yang bersumber dari kisah Panji, pangeran legendaris dari Jawa Timur. Jika wayang purwa (yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana) menjadi bentuk paling populer, maka wayang gedhog pernah berjaya di lingkungan istana sebelum perlahan menghilang dari panggung masyarakat. Sejarahnya memperlihatkan bagaimana kebudayaan Jawa terus beradaptasi seiring perubahan zaman.
Dari Epos India ke Legenda Lokal
Sebelum kisah Panji populer, pertunjukan wayang mengisahkan cerita nenek moyang dan kemudian menyerap epos besar India. Pada abad ke-9, relief Candi Prambanan sudah memvisualkan kisah Ramayana dan Kresnayana, bukti bahwa wayang menjadi medium penting untuk mitologi Hindu-Buddha. Prasasti-prasasti kuno pun mencatat pertunjukan wayang yang dipersembahkan untuk arwah leluhur.
Di masa Raja Darmawangsa (abad ke-11), dikenal semboyan mangjawaken Byasamata—“menjawakan ajaran Vyasa” (pengarang Mahabharata). Artinya, karya India tidak hanya diterjemahkan ke bahasa Jawa Kuna, tetapi juga diolah sesuai dengan nilai lokal. Kakawin seperti Arjunawiwaha dan Bharatayuddha bukan hanya karya sastra, tetapi juga sumber lakon wayang. Namun, memasuki abad ke-14, masyarakat mulai jenuh dengan kisah berbahasa Sanskerta. Muncullah tradisi kidung dalam bahasa Jawa Pertengahan yang lebih dekat dengan rakyat, menampilkan pahlawan lokal, terutama Panji.
Munculnya Kisah Panji
Kisah Panji menceritakan pengembaraan Raden Panji dari Janggala yang terpisah dari kekasihnya, Dewi Candra Kirana dari Kediri. Dalam berbagai penyamaran, Panji menempuh perjalanan penuh rintangan hingga akhirnya bersatu kembali dengan sang pujaan hati. Pada masa Majapahit, kisah Panji mencapai puncak popularitasnya. Ia hadir dalam kidung, tari-tarian rakyat, hingga wayang gambuh. Dari sinilah tumbuh bentuk seni pertunjukan yang kelak dikenal sebagai wayang gedhog. Cerita Panji kemudian menyebar ke Bali, Lombok, bahkan sampai ke Thailand dan Kamboja, menandakan luasnya pengaruhnya.
Apa Itu Wayang Gedhog?
Asal-usul kata gedhog masih diperdebatkan. Ada yang mengaitkannya dengan gedhogan (kandang kuda), karena banyak tokoh Panji berawalan “kuda-”. Ada juga yang menghubungkannya dengan bunyi dhodhogan (ketukan kotak dalang), atau gedheg (batas/pemisah) yang menandai perbedaan antara cerita purwa dan cerita Panji. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan kedhok (topeng), sebab kisah Panji juga dimainkan dalam seni topeng.
Apapun asal katanya, wayang gedhog didefinisikan sebagai pertunjukan wayang kulit dengan cerita Panji. Ciri-cirinya:
- Tokoh utama Panji memakai tutup kepala tekes dan bersenjatakan keris.
- Musuh utama adalah Prabu Klana dari negeri seberang, dengan pasukan Bugis, Bali, atau Makassar.
- Menggunakan laras gamelan pélog.
- Bentuk boneka bervariasi sesuai daerah (Yogyakarta, Surakarta, Madura, Kediri).
Wayang Gedhog pada Era Islam dan Mataram
Masuknya Islam tidak mematikan wayang, justru memberi nafas baru. Tradisi menisbatkan munculnya wayang gedhog abad ke-16 pada Sunan Giri II, sebagai media dakwah. Pada masa Sultan Agung (abad ke-17), wayang gedhog menjadi bagian penting seni istana.
Meski sempat surut akibat pemberontakan Trunajaya, wayang gedhog kembali bangkit pada abad ke-18 di Surakarta. Para raja membuat perangkat wayang megah seperti Kyahi Banjed dan Kyahi Dewakatong yang berfungsi sebagai pusaka kerajaan. Di luar keraton, varian lokal juga berkembang: wayang sasak di Lombok, wayang takul di Banyuwangi, hingga catatan tentang pertunjukan di Banten.
Dengan demikian, wayang gedhog tidak hanya seni istana, tetapi juga bagian dari budaya masyarakat luas.
Wayang Gedhog di Yogyakarta
Peristiwa Palihan Nagari tahun 1755 membelah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwana I di Yogyakarta dikenal sebagai raja ksatria sekaligus seniman besar. Ia menciptakan berbagai tarian dan tokoh wayang, dan turut mengembangkan wayang gedhog.
Pada masa Hamengkubuwana II hingga V, wayang gedhog semakin dipoles: bonekanya diperbesar dan tatahannya diperhalus. Bahkan muncul varian unik, wayang tepèn, yang menampilkan Panji dengan berbagai ikat kepala. Pertunjukan digelar dalam upacara keraton, malam tirakatan, atau pesta pernikahan.
Namun, karena bahasanya dianggap terlalu “kasar”, dalang dari Pakualaman kerap dipanggil untuk mementaskannya. Versi Pakualaman pun memiliki ciri berbeda, misalnya busana tokohnya lebih mirip wayang purwa. Perbedaan halus ini memperlihatkan kreativitas masing-masing istana.
Kemunduran Wayang Gedhog
Memasuki abad ke-19, pamor wayang gedhog mulai meredup. Penyebabnya beragam:
- Manuskrip dan perangkat wayang banyak hilang atau rusak.
- Minimnya regenerasi dalang.
- Masyarakat lebih mengenal dan menyukai wayang purwa.
Pada abad ke-20, pentas wayang gedhog hanya sesekali diadakan, lebih sebagai tontonan budaya daripada tradisi hidup. Beberapa dalang Surakarta bahkan didatangkan untuk mementaskannya di Yogyakarta atau Pakualaman. Meski begitu, masih ada upaya kecil di sekolah, balai bahasa, atau komunitas seni untuk mempertahankannya.eberapa dalang Surakarta bahkan didatangkan untuk mementaskannya di Yogyakarta atau Pakualaman. Meski begitu, masih ada upaya kecil di sekolah, balai bahasa, atau komunitas seni untuk mempertahankannya.
Penemuan Kembali Lewat Naskah
Harapan untuk memahami wayang gedhog kembali muncul berkat naskah kuno yang tersimpan di luar negeri.
- Perpustakaan Universitas Leiden menyimpan naskah Or. 6428 yang berisi 51 lakon Panji, disalin pada 1906 dari sumber lebih tua.
- British Library di London memiliki naskah MSS Jav 44 dan 62 dari akhir abad ke-18, yang menggambarkan gaya awal Yogyakarta.
Naskah-naskah ini memperlihatkan dua jenis cerita: kisah percintaan non-siklus (Panji dan Candra Kirana dalam berbagai penyamaran) dan kisah siklus (Panji sebagai leluhur raja-raja Jawa). Ada juga pengaruh wayang purwa, misalnya tokoh Prabu Klana atau adegan mirip lakon Dewa Ruci.
Tanpa manuskrip-manuskrip ini, hampir semua detail tentang wayang gedhog mungkin sudah hilang.
Narasi dan Dramaturgi
Struktur pertunjukan wayang gedhog menyerupai wayang purwa, tetapi dengan warna tersendiri.
Jenis Cerita
- Non-siklus: fokus pada pengembaraan Panji dan kisah cintanya, biasanya berakhir dengan pertemuan kembali.
- Siklus: menggambarkan Panji sebagai tokoh historis, beranak cucu, mewariskan tahta.
Pola Pertunjukan
- Adegan pembuka (jejer) di istana.
- Perjalanan Panji dalam penyamaran.
- Konflik dengan Prabu Klana dan pasukan Bugis.
- Adegan lawakan Bancak-Dhoyok.
- Pertempuran klimaks dan penyatuan kembali Panji–Candra Kirana.
Musik menggunakan laras pélog dengan gendhing khas seperti Kombang Mas dan Kemong-Kemong. Sulukan dalang berisi pujian pada raja atau doa kepada Sang Hyang Wasesa, menegaskan nuansa sakral pertunjukan.
Makna dan Relevansinya di Masa Kini
Wayang gedhog adalah cermin perjalanan budaya Jawa: dari epos India menuju legenda lokal, dari Hindu-Buddha ke Islam, dari seni rakyat ke seni istana.
Kini, keberadaannya sangat rapuh. Dalang yang menguasai repertoar Panji bisa dihitung dengan jari, dan peminatnya terbatas. Namun upaya revitalisasi tetap berjalan. Proyek digitalisasi Leiden dan British Library membuat naskah Panji dapat diakses siapa saja. Beberapa pertunjukan rekonstruksi digelar untuk memperkenalkan kembali genre ini.
Menghidupkan wayang gedhog bukan sekadar melestarikan kesenian langka, melainkan merawat imajinasi budaya Jawa tentang cinta, pengembaraan, penyamaran, dan takdir.
Penutup
Wayang gedhog adalah bayangan sekaligus cahaya: bayangan karena hampir punah, cahaya karena menyingkap kekayaan imajinasi Jawa. Dari kisah Panji yang penuh cinta dan petualangan, dari istana ke perpustakaan asing, dari panggung keraton ke arsip digital, kita bisa melihat betapa lenturnya tradisi wayang menghadapi perubahan zaman.
Meski jarang dipentaskan, wayang gedhog tetap penting untuk memahami jati diri Jawa—sebuah warisan kreatif yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Selama bayangan Panji masih ada di layar kelir, sejarah pun masih hidup.






Gallery
Untuk gambar dengan resolusi tinggi dan dokumentasi wayang Gedhog yang komplit, silahkan hubungi kami.